Refleksi
Sunday, June 03, 2018
Pantulan cermin di kamar mandi hotel kala itu mengagetkan saya. Dengan tampilan rambut baru yang dengan nekatnya saya pangkas sendiri hingga di atas bahu, mata sembab karena terbangun tengah malam, dan tubuh yang berbalut daster hijau bercorak bunga putih, saya pikir saat itu saya sedang melihat almarhumah mama.
Padahal orang bilang wajah saya sama sekali tidak beririsan dengannya. Entah benar entah tidak. Yang jelas saya setuju jika hidung besar saya merupakan fitur istimewa yang diwariskan dari papa. Satu bagian itu saja rasanya sudah cukup untuk membuat orang seantero jagad yakin kalau bapak yang satu itu merupakan ayah kandung saya.
Namun di tengah malam itu, untuk sepersekian detik, refleksi saya menyuguhkan gambaran lain. Saya melihat mama di diri saya.
Aegyo sal, atau tumpukan lemak di bawah mata ini, tentu tidak seperti mata papa. Ditambah dengan kantung mata yang menghitam di bawahnya, lagi-lagi tak mungkin dimiliki oleh ayah saya yang selalu terlelap di jam yang sama setiap harinya. Juga wajah yang seolah lupa dirawat ini, lebih mengingatkan saya akan wajah mama. Tak perlu lah saya menyebutkan rambut pendek dan daster yang saya kenakan kala itu. Karena hanya merupakan copy paste dari penampilan sehari-hari mama di rumah.
Sepersekian detik refleksi itu, cukup untuk membuat saya merenungi kembali peristiwa-peristiwa yang lalu. Ketika saya baru kembali merantau dari tanah Melayu misalnya, terbesit pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Mengapa mama menua begitu cepat? Garis kerutnya, kulitnya yang mulai menurun, kesehatannya yang berada di titik nadir. Hati saya bergejolak. Mungkin hampir setiap anak pernah merenungi hal ini. Tapi menjadi menyesakkan saat saya menyadari bahwa di sisi lain, papa terlihat immortal, wajahnya begitu-begitu saja. Jikalau pun terlihat sedikit menua, ia menua dengan elegan.
Kenapa waktu seakan mempermainkan kecantikan mama?
***
Saya ingat betul segala cekcok dan perang fisik maupun batin yang terjadi antara saya dan mama, atau antara adik saya yang nomor dua dengan mama, atau si bungsu dengan mama. Karakter beliau sungguh unik, seakan bisa menyulut api amarah siapapun yang berbicara dengannya.
Di mata mama, saya adalah anak nakal, buruk perangainya, dan suka melawan.
Kalau saya pulang malam karena aktif di organisasi, saya malah dicecar penuh curiga, dikirinya saya habis berkumpul bersama remaja tidak benar. Jika saya ingin menjalani hobi naik gunung, maka ia tidak akan meridhoi dan meyakinkan kalau saya bisa mati di sana.
Tentu saya protes dengan doa buruk tersebut, tapi lalu saya dianggap pembangkang. Padahal nakalnya saya kala SMA hanya sebatas menulis contekan di kertas kecil. Berbeda dengan mama yang sering membakar uang dengan menghembuskan asap tembakau sejak bangku sekolah.
Hanya ada satu waktu dimana tiba-tiba saya menjadi anak baik yang disanjung, dipuja setinggi langit, melebihi kapasitas saya. Yaitu ketika mama berbincang dengan orang tua lain. Ia tidak mau kalah.
***
Tangis Kautsar, anak saya, pecah di tengah malam, memanggil-manggil nama saya. Lamunan saya pun terbelah. Saya bergegas kembali ke kamar untuk menenangkannya. Tidur di hotel tak lantas membuat saya menikmati 100% suasana liburan. Kegiatan parenting dan pengasuhan tetap harus terlaksana, hanya lokasinya saja yang berbeda.
Sejak dua setengah tahun lalu, tidak ada tidur nyenyak bagi saya. Tak ada suasana makan dengan tenang. Selalu ada kerusuhan kecil yang kadang lucu, kadang juga mengesalkan di meja makan. Dan setiap hari ada saja nasi dan lauk yang berserakan. Saya lelah, tapi tak lantas membuat saya pantas merasa telah berkorban, karena si kecil tak pernah merengek meminta kehidupan.
Dua setengah tahun ini, bisa jadi merupakan refleksi kejadian lampau, lebih dari 20 tahun silam, saat saya masih belia. Saya yakin, pasti saya juga pernah menangis atau mengigau tengah malam, lalu menyebut nama mama untuk sekadar mencari kehangatan dan perlindungan. Pasti saya pernah mengacaukan hatinya dan harinya, membuatnya kelelahan karena merawat saya hingga akhirnya tak sempat merawat kecantikannya sendiri, juga membuatnya merasa kehilangan dirinya yang sejati.
Menjadi ibu dari Kautsar, membangkitkan syukur sekaligus penyesalan di jiwa saya. Bersyukur karena akhirnya, dengan cara ini, saya bisa merasakan seberapa besar cinta mama kepada saya. Cinta yang juga saya rasakan kepada Kautsar.
Dan menyesal karena saya tidak mengetahuinya lebih awal. Mengapa otak belia saya tidak bisa merekam kasih sayangnya dalam memori jangka panjang? Mengapa saya tidak bisa memutar balik peristiwa bahagia saat ia merayakan keberhasilan saya belajar berjalan? Tidak bisa pula mengingat kata-kata pertama yang ia ajarkan, serta perlakuan mulia yang ia tanamkan?
Sedangkan otak remaja saya, bisa mengingat dengan detail segala cela dan kekurangnya? Serta seluruh perkataan menyakitkannya?
***
Sepersekian detik refleksi itu, cukup untuk membuat saya mundur kebelakang. Namun kini saya bisa melihat dengan lebih jelas betapa pentingnya mama dalam kehidupan dan dalam membentuk pribadi saya. Tanpa disadari, mungkin saja kebaikan dan nilai-nilai luhur yang orang lain lihat ada pada diri saya, merupakan pantulan cahaya kebaikan mama.
***
Sambil mengelus-elus punggung Kautsar agar kembali tertidur, saya membisikkan berbagai doa kepada yang Maha Mendengar untuk mama. Semoga ia selalu berbagia di sana.





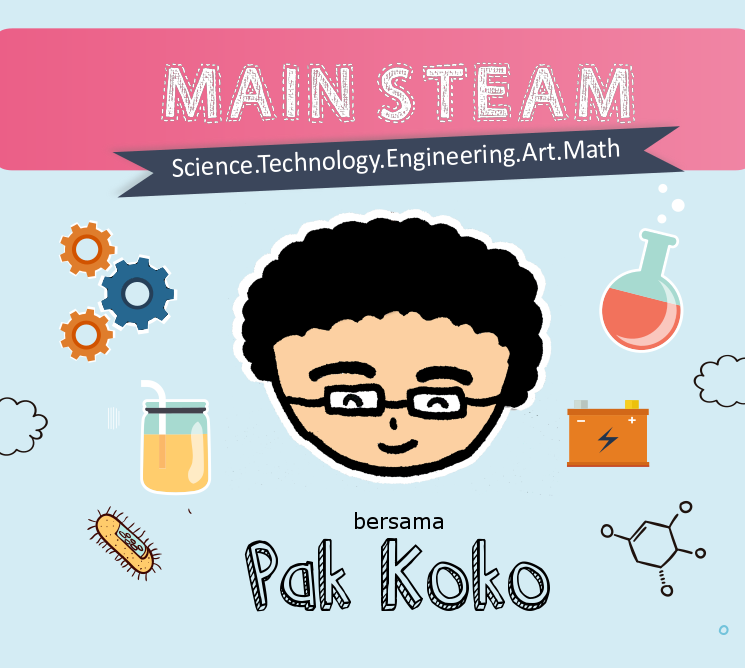


1 comments
😢😢😢😢
ReplyDelete